

Presiden Prabowo Subianto mengejutkan publik saat mengumumkan rencana menjadikan Bahasa Portugis sebagai salah satu disiplin bahasa yang akan diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia. Wacana itu disampaikan ketika ia menjamu Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
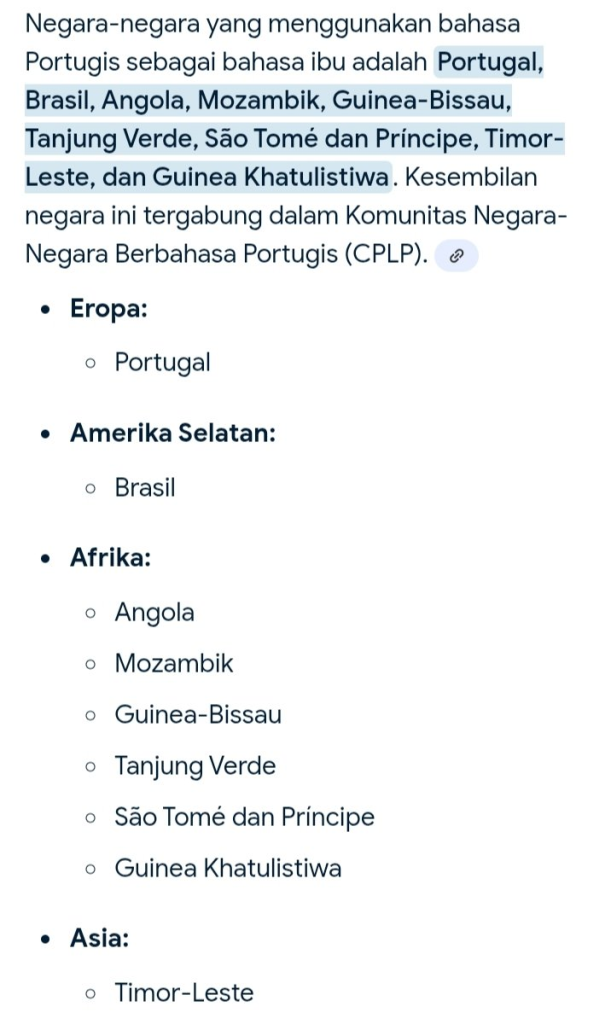
Menurut Prabowo, pengenalan Bahasa Portugis penting karena Brasil dianggap mitra strategis Indonesia, baik dalam hubungan ekonomi, politik global Selatan-Selatan, maupun kerja sama perdagangan. Namun, pertanyaan besar segera muncul: seberapa realistis ambisi ini bisa diwujudkan dalam masa jabatannya yang terbatas, 2024–2029?
1. Bahasa Portugis: Brasil vs. Eropa
Hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa Bahasa Portugis memiliki dua varian utama: Portugis Brasil dan Portugis Eropa.
Secara umum, keduanya sama-sama disebut “Bahasa Portugis” (língua portuguesa). Perbedaan utamanya ada pada:
- Aksen dan fonologi: Portugis Brasil terdengar lebih terbuka dan vokal-vokalnya jelas, mirip dengan bahasa Latin modern. Portugis Eropa cenderung lebih “tertutup” dan cepat.
- Kosakata: Ada variasi kosakata sebagaimana perbedaan antara bahasa Inggris Amerika dan Inggris Britania. Misalnya, “ônibus” (Brasil) = “autocarro” (Portugal) untuk kata “bus”.
- Ejaan: Setelah reform ortografi 2009, perbedaan tulisan sebagian berkurang, tapi tetap ada variasi.
Jika wacana ini diterapkan, kemungkinan besar yang akan dipilih Indonesia adalah Bahasa Portugis Brasil, karena hubungan bilateral saat ini berfokus pada Brasil, bukan Portugal.
2. Kapan SMA Indonesia Bisa Belajar Portugis?
Pertanyaannya: berapa cepat bahasa baru bisa masuk ke SMA/SMU Indonesia?
Realitanya, Indonesia baru memiliki kurikulum bahasa asing tambahan berupa Bahasa Mandarin, Jepang, Jerman, Prancis, Korea, dan Arab. Itu pun terbatas di sekolah-sekolah tertentu dengan SDM guru yang tersedia.
Jika Portugis ingin masuk:
- Jangka pendek (2026–2027): Mustahil langsung diterapkan secara luas. Tidak ada guru yang siap, bahkan program studi sastra Portugis pun belum tersedia di universitas negeri besar Indonesia.
- Jangka menengah (2030): Jika mulai tahun ajaran 2026 sudah dibuka Program Studi Sastra Portugis di UI, UGM, atau eks-IKIP (UNJ/UPI), maka lulusan S1 pertama baru tersedia sekitar 2030. Barulah tersedia guru-guru untuk SMA.
- Jangka panjang (2035 ke atas): Program bahasa Portugis baru bisa berjalan mapan, dengan buku teks, kurikulum, dan dosen/guru yang cukup.
Dengan kata lain, jika Prabowo ingin melihat hasil nyata dalam periode 2024–2029, itu hampir mustahil. Paling jauh, yang bisa ia lakukan adalah meletakkan fondasi awal berupa:
- Membuka program studi Bahasa/Sastra Portugis di beberapa universitas negeri (UI, UGM, UPI, UNJ).
- Mengirim mahasiswa Indonesia ke Brasil atau Portugal untuk studi bahasa dan sastra.
- Menjalin kerja sama budaya dengan Brasil, termasuk pertukaran guru dan beasiswa.
3. Sastra Asing di Indonesia: Kekosongan Portugis
Saat ini, di Indonesia sudah tersedia sastra asing utama:
- Sastra Inggris, Jepang, Prancis, Jerman, Arab, Rusia, Korea
- Beberapa kampus juga punya studi Mandarin, Belanda, Italia.
Namun tidak ada program sastra Portugis. Artinya, belum ada dosen tetap, belum ada kurikulum, dan tidak ada penerbitan karya sastra Portugis dalam bahasa Indonesia (kecuali sedikit terjemahan karya José Saramago dari Portugal atau Paulo Coelho dari Brasil).
Kekosongan ini adalah kendala sekaligus peluang. Jika benar dibuka, Program Studi Sastra Portugis bisa menjadi pintu masuk bagi karya-karya dunia berbahasa Portugis—dari puisi Fernando Pessoa, novel Paulo Coelho, hingga sastra kontemporer Brasil.
4. Bisakah Kurikulum S1 Sastra Portugis Dibentuk Kilat?
Mari buat simulasi realistis:
- November 2025 – Juni 2026: Penyusunan kurikulum Sastra Portugis, rekrutmen dosen asing (Brasil/Portugal), dan persiapan infrastruktur.
- Juni 2026: Mahasiswa angkatan pertama masuk kuliah.
- 2026–2030: Masa studi 4 tahun (8 semester).
- 2029–2030: Lulusan pertama siap mengajar di SMA/SMU.
Kesimpulannya: jika semua berjalan cepat, tahun 2030 adalah tahun paling awal SMA Indonesia bisa punya guru Bahasa Portugis hasil pendidikan dalam negeri.
5. Faktor Politik: Keberlanjutan Pasca-Prabowo
Masalah besar dari kebijakan bahasa adalah kesinambungan politik. Program Prabowo terbatas pada masa jabatan 2024–2029.
Pertanyaan kuncinya:
- Apakah presiden setelah Prabowo akan melanjutkan program ini?
- Bahasa Portugis bukan bahasa internasional utama (seperti Inggris atau Mandarin) dan belum tentu dianggap prioritas oleh pemerintahan berikutnya.
- Ada risiko program ini berhenti sebagai “legacy project” yang hanya simbolis, bukan program berkelanjutan.
Di sisi lain, jika ada tekanan diplomatik—misalnya Brasil menawarkan beasiswa besar, investasi, atau kerja sama strategis (energi, pertanian, BRICS)—maka presiden berikutnya mungkin tetap mempertahankan program ini.
6. Ambisi atau Feasible?
Jika kita menimbang:
- Kesiapan SDM: Belum ada dosen dan guru.
- Kesiapan infrastruktur: Tidak ada jurusan Sastra Portugis di kampus besar.
- Kesiapan kurikulum sekolah: Butuh minimal 5–10 tahun persiapan.
- Masa jabatan Prabowo: Hanya 2024–2029.
Maka jawabannya: wacana ini lebih bersifat ambisius diplomatis ketimbang rencana pendidikan yang feasible jangka pendek.
Paling jauh, Prabowo bisa memastikan:
- Pembukaan jurusan Sastra Portugis di UI, UGM, atau UPI tahun 2026.
- Pemberian beasiswa ke Brasil/Portugal untuk calon dosen/guru.
- Penyusunan rencana besar yang kelak bisa dijalankan pemerintahan berikutnya.
Penutup
Bahasa Portugis memang penting secara geopolitik: digunakan oleh lebih dari 250 juta orang, menjadi bahasa resmi di Brasil, Portugal, Angola, Mozambik, hingga Timor Leste. Namun dari sisi pendidikan Indonesia, jalan untuk memasukkan bahasa ini ke kurikulum SMA masih panjang.
Ambisi Prabowo tampak lebih sebagai isyarat diplomasi ke Brasil ketimbang rencana pendidikan realistis dalam lima tahun ke depan. Jika benar diwujudkan, buahnya baru bisa dipetik sekitar 2030–2035—jauh setelah Prabowo lengser.
Maka pertanyaan akhirnya adalah: apakah Indonesia siap menanam benih sekarang untuk panen di masa depan, ataukah wacana ini hanya akan jadi catatan kecil dalam sejarah diplomasi pendidikan?